Indonesia sering dianggap sebagai negara yang menjalankan kebijakan luar negeri yang non-blok dan seimbang antara kekuatan global. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam industri nikel, yang menjadi salah satu tulang punggung strategi pembangunan ekonomi Indonesia, negara ini semakin terikat dengan Tiongkok. Sama dengan nasib negara-negara lain yang menghasilkan mineral esensial untuk transisi energi, penguasaan yang signifikan atau bahkan mayoritas pengolahan mineral-mineral itu memang sudah dipegang Tiongkok. Dan hal ini sesungguhnya bukan tanpa konsekuensi bagi kepentingan global dalam memastikan keadilan transisi energi, juga bagi kepentingan Indonesia sendiri.
Pengamatan, dan kekhawatiran, saya atas apa yang terjadi dalam hilirisasi nikel hingga sekarang mendapatkan banyak sekali tambahan informasi dan terutama analisis dari Indonesia, Nickel, and the Political Economy of Polyalignment in the Second Cold War, yang ditulis oleh Trissia Wijaya dan Lee Jones di jurnal terkemuka Third World Quarterly pada penghujung Februari lalu. Artikel tersebut mengeksplorasi bagaimana oligarki politik dan bisnis dalam negeri telah membentuk arah kebijakan industri nikel Indonesia, mengarahkan pada ketergantungan yang mendalam terhadap rantai pasok Tiongkok, sekaligus mengikis hubungan strategis dengan Barat.
Mitos Non-Blok
Wijaya dan Jones membuka penjelasannya dengan apa yang disebut sebagai Perang Dingin Kedua yang sedang berkembang. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin mendominasi wacana global, dan Indonesia kerap digambarkan sebagai negara yang mahir dalam meniti posisi non-blok atau hedging. Doktrin kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan, menghindari keberpihakan yang jelas ke blok Barat yang dipimpin AS atau blok Timur yang dimotori Tiongkok-Rusia.
Namun, di balik tampilan netralitas ini, terdapat realitas yang sesungguhnya lebih kompleks, yang dibentuk oleh ekonomi politik oligarki domestik Indonesia dengan ketergantungannya yang semakin besar pada Tiongkok. Dan ini sangat jelas tergambarkan di sektor pengolahan nikel. Ketergantungan ini, yang didorong oleh ambisi Indonesia untuk membangun rantai pasok kendaraan listrik (EV) domestik, mengungkap batasan dari kebijakan non-blok Indonesia dan tantangan dalam menghadapi Perang Dingin Kedua.
Kebijakan luar negeri Indonesia memang sejak lama ditandai oleh komitmen formal terhadap non-blok. Mulai dari penyelenggaraan Konferensi Bandung tahun 1955 oleh Sukarno, yang menjadi landasan bagi Gerakan Non-Blok, hingga pemerintahan Suharto yang secara de facto berpihak pada AS selama Perang Dingin, Indonesia telah bergerak di antara kutub-kutub kekuatan global yang berbeda. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia terus memproyeksikan citra netralitas, menjalin hubungan dengan AS dan Tiongkok di berbagai bidang.
Di satu sisi, Indonesia telah menandatangani kemitraan transisi energi senilai US$20 miliar dengan G7, sambil juga berpartisipasi dalam Kemitraan Investasi dan Keuangan Hijau Tiongkok senilai kolektif US$100 miliar. Indonesia bahkan telah mengajukan diri untuk bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang dipimpin AS dan menyatakan minat pada Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik, sambil tetap menjadi anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) Tiongkok dan kelompok BRICS+.
Kebijakan luar negeri multi-vektor ini telah membuat banyak pengamat menyimpulkan bahwa Indonesia berhasil melakukan hedging antara AS dan Tiongkok, dengan hati-hati menyeimbangkan keterlibatannya untuk memaksimalkan keuntungan nasional sambil mengurangi risiko. Namun, bagi Wijaya dan Jones, interpretasi tersebut jelas terjebak di permukaan, lantaran mengabaikan kekuatan struktural yang lebih dalam dalam ekonomi politik Indonesia, terutama pengaruh oligarki elite yang kuat, yang telah mengarahkan strategi pembangunan ekonomi negara ke arah ketergantungan yang hampir eksklusif pada investasi dan pasar Tiongkok.
Hilirisasi Nikel dan Dominasi Oligarki
Nikel, mineral kritis yang penting untuk produksi baterai EV, telah menjadi pusat strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan memiliki 42% cadangan nikel dunia yang kini sudah diketahui, Indonesia berupaya memanfaatkan sumber daya alamnya untuk naik dalam rantai nilai, dari mengekspor bijih nikel mentah hingga mengembangkan rantai pasok EV yang lengkap. Pemerintah telah menerapkan serangkaian kebijakan untuk menarik investasi asing dalam pengolahan nikel hilir, termasuk larangan ekspor bijih nikel mentah dan insentif untuk pembangunan smelter. Kebijakan ini merupakan bagian sentral dari Visi 2045 Indonesia, yang bertujuan mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun tahun tersebut.
Di permukaan, pendekatan Indonesia untuk mencapai visi tersebut tampak mengikuti strategi hedging, dengan menarik investasi dari semua ekonomi besar, termasuk AS, Jepang, dan Eropa, sambil menghindari ketergantungan pada satu kekuatan eksternal. Namun, kenyataan sesungguhnya jauh lebih timpang. Meskipun upaya untuk menarik investasi Barat, investor dan perusahaan Tiongkok telah secara nyata mendominasi sektor nikel Indonesia, menyumbang sekitar 90% investasi hilir dan 80-82% produksi nikel kelas baterai. Tiongkok juga mendominasi ekspor berbasis nikel Indonesia, mengambil 98% nilainya pada pertengahan 2023.
Dominasi investasi Tiongkok di sektor nikel Indonesia bukan sekadar hasil dari keunggulan struktural Tiongkok di pasar nikel global yang memang nyata demikin, tapi juga merupakan produk dari ekonomi politik domestik Indonesia, terutama pengaruh oligarki politiko-bisnis. Oligarki ini, yang muncul selama era otoriter Suharto, dan setelah itu beradaptasi dengan negara pasca-otoriter, memiliki kekuatan signifikan atas pembuatan kebijakan dan alokasi sumber daya. Kepentingan oligarki telah membentuk pengembangan nikel Indonesia dengan cara yang mengutamakan keuntungan jangka pendek dan pengayaan elite daripada pembangunan nasional jangka panjang, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat sosial dari hilirisasi.
Menurut Wijaya dan Jones, terdapat tiga kelompok elite, yang tumpang tindih, benar-benar diuntungkan dari pengembangan nikel: perusahaan domestik besar, elite politik, dan konglomerat batubara. Banyak miliarder teratas Indonesia terlibat dalam pertambangan atau pengolahan nikel, sering kali melalui kemitraan dengan investor Tiongkok. Elite politik, termasuk tokoh-tokoh kunci dalam kabinet Jokowi, juga mengembangkan kepentingan terkait nikel yang signifikan. Misalnya, Menteri Investasi (kemudian menjadi Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia dinyatakan memiliki tambang nikel, sementara Menteri Koordinator Luhut Pandjaitan disebut memiliki saham di perusahaan EV. Elite ini telah menggunakan posisi mereka untuk membentuk kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka, seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang mengurangi regulasi ketenagakerjaan dan lingkungan untuk menarik investasi asing.
Industri batubara, yang menghadapi penurunan jangka panjang karena transisi hijau global, juga menemukan jalur hidup dalam pengembangan nikel. Pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) demi mendukung pengolahan nikel yang membutuhkan energi besar telah dibenarkan sebagai kebutuhan untuk pertumbuhan industri, meski dengan biaya lingkungan yang tinggi. Pembangunan berbagai PLTU untuk hilirisasi nikel ini, yang sudah menyumbang 15% dari pasokan listrik berbasis batubara Indonesia, diperkirakan akan terus berkembang, jelas bertentangan dengan komitmen iklim Indonesia dan selain tak sesuai dengan tujuan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) G7.
Kegagalan Hedging, Peningkatan Ketergantungan pada Tiongkok
Upaya Indonesia untuk hedging antara AS dan Tiongkok jelas gagal di sektor nikel. Meski pemerintah seperti berusaha menarik investasi dari semua pihak, kenyataannya perusahaan Tiongkok telah mendominasi, berkat kesediaan mereka untuk bermitra dengan elite ekonomi dan Indonesia sesuai persyaratan yang diminta, dan menoleransi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang buruk. Sebaliknya, perusahaan dari AS dan Eropa terhalang oleh kekhawatiran atas kondisi pengelolaan ESG di perusahaan-perusahaan Indonesia, selain karena kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah. Sengketa WTO Uni Eropa terhadap larangan ekspor nikel Indonesia, dan pengecualian perusahaan yang memberikan investasi dari Tiongkok dari kredit pajak EV dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, semakin meminggirkan keterlibatan Barat di sektor nikel Indonesia.
Hasil yang timpang ini punya implikasi signifikan bagi masa depan Indonesia. Dengan mengikat diri pada rantai pasok yang didominasi Tiongkok, Indonesia berisiko menjadi semakin bergantung pada Tiongkok. Tidak hanya secara ekonomi, melainkan juga secara politik. Ketergantungan ini jelas dapat membatasi kemampuan Indonesia mempertahankan kebijakan luar negeri yang seimbang, terutama ketika ketegangan antara AS dan Tiongkok meningkat—dan memang diperkirakan begitu di bawah kepemimpinan Presiden Trump yang eratik. Selain itu, biaya lingkungan dan sosial dari penambangan dan pemrosesan nikel, termasuk namun tidak terbatas pada deforestasi, polusi, dan pemindahan masyarakat lokal, mengancam untuk merusak tujuan pembangunan yang ingin dicapai pemerintah.
Pengalaman Indonesia dengan hilirisasi nikel jelas menunjukkan keterbatasan komitmen polyalignment dalam masa Perang Dingin Kedua ini. Meskipun doktrin kebijakan luar negeri formal Indonesia menekankan non-blok dan pengembangan kemitraan eksternal yang beragam, kenyataan yang sekarang terpampang adalah faktor ekonomi politik domestik—terutama pengaruh oligarki elite—telah mengarahkan strategi pembangunannya ke arah ketergantungan pada Tiongkok. Ketergantungan ini, yang sangat jelas dipaparkan oleh Wijaya dan Jones didorong oleh pencarian keuntungan jangka pendek dan pengayaan elit, merusak tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia dan mereduksi kemampuan Indonesia untuk menghadapi kompleksitas persaingan kekuatan besar.
Dalam mengejar Visi 2045-nya Indonesia jelas harus menghadapi beragam tantangan yang ditimbulkan oleh ekonomi politik domestik dan struktur global di mana ia berada. Dan dari artikel menyimpulkan bahwa tanpa reformasi signifikan untuk mengatasi pengaruh oligarki, dan kesungguhan menekan biaya lingkungan dan sosial dari pengembangan nikel, bahkan bersikeras untuk memastikan optimalisasi manfaat lingkungan dan sosialnya, Indonesia berisiko menjadi pion dalam Perang Dingin Kedua, alih-alih menjadi penguasa atas nasibnya sendiri. Ilusi non-blok, seperti ditunjukkan dalam konteks hilirisasi nikel jelas adalah ilusi yang berbahaya, lantaran menyembunyikan kekuatan yang lebih dalam yang membentuk hubungan eksternal dan masa depan ekonomi Indonesia.
Merenungi Nikel, Menimbang Artikel
Buat saya, artikel ini sangat berhasil mengangkat persoalan sangat strategis dalam industri nikel Indonesia dengan sudut pandang kritis terhadap ekonomi politik dan geopolitik. Salah satu kekuatan utama artikel ini adalah kemampuan Wijaya dan Jones mengaitkan kebijakan ekonomi nasional dengan dinamika global, khususnya dalam konteks ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara Barat. Pembahasan tentang polyalignment menjadi relevan karena menggambarkan dilema Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan global sambil tetap mengembangkan sektor industrinya.
Saya sangat menyukai gaya penulisan artikel ini yang lugas, dengan argumen yang didukung oleh sumber pustaka dan analisis mendalam tentang bagaimana oligarki politik dan bisnis dalam negeri membentuk kebijakan industri nikel. Penekanan pada dominasi luar biasa dari investor dan perusahaan asal Tiongkok juga memberikan perspektif yang tajam mengenai risiko ketergantungan ekonomi yang berpotensi membatasi fleksibilitas Indonesia dalam kebijakan luar negeri.
Di sisi lain, saya memiliki harapan untuk mendapatkan data yang lebih konkret. Misalnya, ketika membahas dominasi Tiongkok, artikel menyebutkan bahwa investasi dari negara tersebut lebih tinggi dibandingkan dari Barat. Jelas hal itu benar adanya, tetapi saya akan jauh lebih puas bila terdapat angka spesifik, juga perbandingan asal investasi, di antara perusahaan-perusahaan pertambangan dan smelter nikel di Indonesia. Memasukkan data tentang persentase kepemilikan dan pembiayaan domestik dan asing dari berbagai negara dalam industri nikel jelas akan memberikan bobot lebih pada argumen yang diajukan.
Selain itu, artikel ini mungkin dapat memperkaya pembahasannya dengan memberikan contoh perusahaan atau projek tertentu yang mencerminkan dominasi Tiongkok dan bagaimana oligarki Indonesia mengambil keuntungan dari situasi ini. Sebagai contoh, menyebutkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan mayoritas oleh Tiongkok juga menguraikan lebih lanjut mengenai regulasi yang memungkinkan struktur kepemilikan tersebut akan memperkuat narasi yang dibangun.
Lebih jauh lagi, bila ada bagian khusus yang membandingkan bagaimana kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial perusahaan-perusahaan yang didominasi modal Tiongkok versus yang lainnya. Sebagai orang yang telah mondar-mandir di beragam lokasi industri nikel di Indonesia, saya meyakini bahwa data kinerja itu akan memihak pada kesimpulan yang telah dibuat Wijaya dan Jones.
Terakhir, saya berpendapat bahwa bagian solusi di akhir artikel juga dapat dikembangkan lebih jauh. Artikel ini telah menyebutkan secara umum bahwa Indonesia perlu meningkatkan tata kelola industri dan memperkuat standar ESG. Mungkin akan lebih baik bila ada beragam rekomendasi langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu hal yang saya bayangkan akan menarik adalah juga menghadirkan contoh negara lain yang berhasil mengelola industri strategisnya tanpa jatuh ke dalam ketergantungan, atau yang menguatkan penegakan ESG dan berhasil menarik investor dan perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan.
Secara keseluruhan, artikel ini sangatl memuaskan karena memiliki fondasi analisis yang kuat dan sudut pandang yang tajam. Dengan tambahan data yang lebih konkret dan solusi yang lebih operasional, artikel ini dapat menjadi kajian yang lebih berpengaruh dalam perdebatan tentang masa depan industri nikel dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Bacaan terkait
Hilirisasi Nikel di Indonesia: Peluang Keberlanjutan atau Ancaman Jangka Panjang?
Apakah Prabowo Menghidupkan Kembali Rezim Soeharto?
Menyingkap Tiga Langkah Strategis Kebangkitan Tiongkok
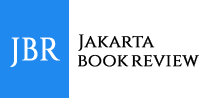
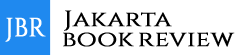




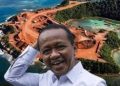



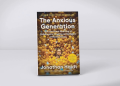



Ulasan Pembaca 2