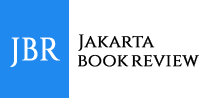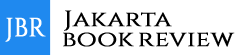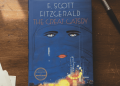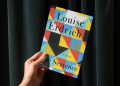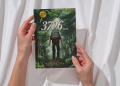“Om, sebetulnya bad mining itu kayak apa, sih? Yang good juga gimana?” Begitu pesan yang saya terima dari seorang rekan di minggu lalu. Saya tak perlu menebak-nebak dari mana pertanyaan itu muncul, karena debat tentang pertambangan di Raja Ampat memang sedang hangat-hangatnya. Dan seorang ahli dalam ilmu agama mengeluarkan pendapat bahwa pertambangan yang tak boleh dilakukan itu adalah yang bad mining, tanpa menjelaskan secara memadai apa yang dia maksud itu.
Industri pertambangan sendiri telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang signifikan terhadap PDB, devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, secara umum reputasinya sering kali diwarnai oleh tantangan serius terkait dampak lingkungan, konflik sosial, dan isu tata kelola. Di tengah desakan global menuju praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, Indonesia berada di persimpangan jalan krusial: apakah akan terus bergulat dengan praktik pertambangan yang buruk dan tidak patuh pada regulasi; sekadar memenuhi standar minimal sesuai regulasi ketinggalan zaman yang sekarang berlaku; atau berani melangkah lebih jauh menuju praktik pertambangan yang setara dengan standar internasional, demi keberlanjutan masa depan?
Mengapa saya bagi menjadi tiga dan bukannya dua pertentangan diametrikal antara pertambangan yang buruk dan baik? Mungkin karena pengalaman saya di lapangan selama 3 dekade mengamati secara lekat industri pertambangan mengajarkan kepada saya nuansa yang lebih subtil daripada pembedaan yang mengaburkan kondisi. Mengapa kemudian saya menamai tiga kategori pertambangan yang ada sebagai ugly, bad, dan Okay—bukan ugly, bad, dan good yang jelas diilhami oleh film koboi terkenal itu? Ini juga lantaran saya belum melihat praktik dan kinerja pertambangan yang benar-benar bisa dinyatakan sebagai good.
Ada memang istilah good mining practice (GMP), tetapi kalau saya tanyakan kepada para pegiat pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk yang bekerja di dalam industri ini, apa yang termaktub di dalamnya—apalagi praktiknya—belumlah benar-benar bisa dibilang good. Ada terlampau banyak aspek keberlanjutan yang diabaikan di situ. Jadi, alih-alih good, saya pergunakan saja istilah okay, yang mengimplikasikan masih luasnya ruang perbaikan.
Izinkan saya, dengan berterima kasih dan meminta maaf kepada Sergio Leone, untuk menguraikan apa yang saya maksudkan dengan ketiga tingkatan itu sebagai berikut:
Ugly Mining adalah Ancaman yang Nyata
Praktik pertambangan yang sangat buruk rupa (Ugly) ditandai dengan ketidakpatuhan atau pelanggaran terang-terangan terhadap regulasi nasional Indonesia, yang mengakibatkan kerugian meluas dan mendalam. Secara lingkungan, dampaknya sangat menghancurkan. Di berbagai lokasi pertambangan kita masih kerap menyaksikan pembuangan limbah tanpa izin, seperti pembuangan tailing ke sungai atau laut tanpa pengolahan yang memadai, yang menyebabkan pencemaran air dan kerusakan ekosistem akuatik.
Operasi penambangan nikel di berbagai tempat di Sulawesi—tidak seluruhnya!—telah mengakibatkan sedimentasi parah, polusi air, dan bahkan kolapsnya kolam pengendapan, menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan lingkungan dasar. Di Halmahera, deforestasi masif dan pembuangan air panas serta limbah ke sungai dan laut akibat pertambangan nikel, sering diperparah dengan penggunaan PLTU batu bara yang tak memenuhi baku mutu udara, menambah daftar panjang kasus-kasus penghancuran lingkungan. Belum lagi lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja tanpa reklamasi, menjadi jebakan mematikan dan lahan tak produktif.
Secara sosial, praktik-praktik ini sering kali berujung pada perampasan lahan tanpa kompensasi yang adil, pemindahan paksa masyarakat adat, dan konflik sosial yang meluas. Kasus-kasus di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi di mana masyarakat adat dan lokal menghadapi kriminalisasi karena mempertahankan hak-hak mereka, adalah bukti nyata dari pengabaian hak asasi manusia. Kondisi kerja yang tidak aman, upah rendah, dan penolakan hak berserikat juga menjadi ciri khas praktik ini.
Dari sisi tata kelola, masalah korupsi dalam proses perizinan adalah akar masalah yang merusak, di mana pejabat daerah memberikan izin tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan atau sosial, dan praktik suap untuk memanipulasi penilaian dampak lingkungan (AMDAL) bukanlah hal asing. Kasus penambangan ilegal, transaksi fiktif, dan penyalahgunaan dana pengembangan masyarakat, menunjukkan betapa parahnya tata kelola yang buruk dapat merusak integritas industri dan negara. Secara ekonomi, praktik ini ditandai dengan ekspor ilegal, penghindaran pajak, dan penambangan ilegal yang merugikan pendapatan negara secara signifikan, sering kali hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat setempat maupun negara.
Bad Mining di Garis Batas Kepatuhan
Praktik pertambangan yang saya nyatakan sebagai Bad adalah yang minimalis atau patuh pada persyaratan peraturan nasional Indonesia. UU Minerba 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kerap menjadi kerangka hukum yang membentuk dasar kepatuhan ini. Kalau saya kontraskan kepatuhan ini dengan kinerja di lapangan, saya harus menyatakan bahwa kepatuhan saja hasilnya adalah bad mining. Silakan tanyakan kepada siapa pun yang bergelut di area ini cukup lama, mereka akan bisa dengan fasih menjelaskan beragam lubang yang menganga di setiap peraturan serta bagaimana mengeksploitasinya. Kalau mereka ditanya apa saja ruang perbaikan yang masih diperlukan agar regulasi menjadi lebih baik, mereka bakal nyerocos berjam-jam untuk menjelaskan. Tentu, mereka tak berani terlampau keras menyampaikan kritik kalau di hadapan pemerintah langsung.

Di bidang lingkungan, misalnya, perusahaan yang patuh setidaknya telah memiliki izin lingkungan dan AMDAL, meskipun kualitas studinya bisa bervariasi. Dan ‘variasi’ ini luar biasa besar. Saya beberapa kali menemukan AMDAL yang jelas-jelas copy-paste dari tempat lain dan dinyatakan diterima. Di dunia internasional, membuat AMDAL sesuai regulasi Indonesia itu tidaklah dianggap memadai. Setiap kali ada perusahaan yang mengajukan AMDAL sebagai ganti Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), misalnya untuk mendapatkan pembiayaan dan investasi, setiap kali itu pula akan diminta untuk membuat ESIA.
Banyak perusahaan tambang yang menunjukkan upaya reklamasi pascatambang yang patuh, dengan penataan timbunan limbah, penyebaran lapisan tanah pucuk, dan penanaman tanaman penutup. Namun, tantangan seperti stabilisasi lereng dan komposisi spesies masih sering menjadi pekerjaan rumah yang serius, yang belum benar-benar diatur dalam regulasi kita. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan pun bisa memiliki keterbatasan dalam mencapai restorasi ekologis yang penuh—yang oleh standar internasional kini sudah ditandai misalnya dengan no net loss atau bahkan positive biodiversity impact.
Secara sosial, perusahaan yang patuh menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagaimana diamanatkan oleh UU Minerba, meliputi delapan pilar seperti pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Tetapi, silakan periksa apakah kondisi masyarakatnya setelah bertahun-tahun memang benar meningkat kesejahteraan dan kemandiriannya? Kalau kemudian dinilai dengan kriteria ketangguhan dan keberlanjutan, sudah jelas mayoritas pertambangan akan gagal, walau secara aturan PPM mereka bisa memenuhinya.
Perusahaan pertambangan mematuhi prosedur hukum dalam pengadaan lahan, membayar kompensasi sesuai ketentuan, dan memenuhi standar minimum ketenagakerjaan seperti upah minimum dan keselamatan dasar. Tetapi, silakan periksa lagi apakah kepatuhan yang sama ditunjukkan pada para kontraktornya. Pengalaman saya yang lain menunjukkan komitmen terhadap hak-hak pekerja, perlindungan perempuan, dan kesempatan kerja yang setara ada pada perusahaan-perusahaan tambang yang terkemuka. Namun, di antara mereka yang mematuhi ekspektasi seperti itu pun kerap gagal melangkah lebih jauh untuk memastikan keadilan sosial yang sesungguhnya termasuk FPIC dari masyarakat terdampak. Mengapa? Karena norma yang sebetulnya adalah keniscayaan itu tidak dimasukkan dengan memadai di dalam regulasi pertambangan.
Dalam tata kelola, perusahaan yang patuh memiliki izin yang sah, menyerahkan laporan rutin kepada pemerintah mengenai produksi dan keuangan, serta tunduk pada pengawasan dan sanksi administratif. Keikutsertaan Indonesia dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dengan skor yang masih “cukup rendah,” menunjukkan komitmen pemerintah dan perusahaan untuk mengungkapkan data kontrak dan isu isu ESG secara rutin, yang merupakan langkah kepatuhan dasar menuju transparansi, masih dianggap belum sesuai ekspektasi global. Sistem Clear and Clean (CnC) merupakan upaya untuk memastikan legalitas izin, tetapi kerap dikritik sebagai proses administratif tanpa penilaian lapangan yang mendalam, bahkan oleh pemangku kepentingan di dalam negeri. Lantaran ekspektasi dalam regulasi kita memang rendah, maka mematuhi regulasi—dengan sangat menyesal—harus saya nyatakan masih ada dalam ambang tambang yang buruk.
Merangkul Standar Global untuk Mencapai Okay Mining
Praktik pertambangan yang bisa diterima (Okay—belum sampai Good) dicapai hanya dengan melampaui kepatuhan minimal, mengadopsi standar dan kerangka kerja internasional seperti dari International Council on Mining and Metals (ICMM Mining Principles), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA Standard), International Finance Corporation (IFC Performance Standards), dan PBB (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Pendekatan yang mereka usung berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang, pengelolaan risiko yang holistik, dan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.
Praktik yang mereka promosikan mengedepankan ESIA, yang jauh melampaui AMDAL dasar. Secara lingkungan misalnya dan mengintegrasikan solusi berkelanjutan seperti sistem air tertutup (closed-loop water systems) untuk meminimalkan penggunaan dan pembuangan air. Pengelolaan limbah ditingkatkan dengan teknologi seperti dry stack tailings atau program waste-to-value yang mengubah limbah menjadi sumber daya. Ada juga pernyataan komitmen kuat terhadap konservasi keanekaragaman hayati, termasuk upaya net-positive impact dan perencanaan penutupan tambang terintegrasi yang mencakup rehabilitasi progresif dan penggunaan lahan pascatambang yang beragam.
Di ranah sosial, praktik baik melibatkan Free, Prior, Informed Consent (FPIC) dengan masyarakat lokal dan adat. Ide dasar pengelolaannya tidak loncat langsung ke sekadar kompensasi, tetapi benar-benar pembagian manfaat yang adil. Mekanisme pengaduan yang transparan dan efektif menjadi prioritas, memastikan keluhan ditangani dengan cepat dan adil—dan ini hanya sebagian saja dari praktik yang diharapkan dalam pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Komitmen yang kuat terhadap hak-hak pekerja, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja yang unggul, upah layak yang lebih tinggi daripada minimum, bahkan hingga mempertimbangkan kesehatan mental pekerja. Lebih jauh, praktik yang jelas diharapkan juga mencakup diversifikasi ekonomi masyarakat lokal untuk mengurangi ketergantungan pada tambang setelah penutupan.
Dalam tata kelola, transparansi menjadi pilar utama. Perusahaan tidak hanya mematuhi EITI, tetapi juga proaktif dalam mengungkapkan kontrak, kepemilikan manfaat (beneficial ownership), dan pembayaran kepada pemerintah secara publik. Praktiknya juga mencakup audit independen dan sistem manajemen risiko yang kokoh, termasuk yang berfokus pada hak asasi manusia dan mitigasi konflik. Secara ekonomi, pertambangan diharapkan berinvestasi pada penciptaan nilai lokal yang signifikan, termasuk pengadaan barang dan jasa dari pemasok lokal, pengembangan bisnis kecil dan menengah di sekitar area tambang, serta program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
Praktik-praktik tersebut, bila benar ditegakkan, secara eksplisit ditujukan untuk berkontribusi secara langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Persetujuan Paris—baik di tingkat nasional dan global. Tetapi, mengapa saya masih menyatakannya hanya Okay, bukan Good? Siapa pun yang mau menyelami berbagai ekspektasi standar dan kerangka global itu, pasti masih akan bisa menemukan beragam ruang perbaikan. Belum ada jaminan bahwa masyarakat bakal ada dalam kondisi adil dan berkelanjutan, seandainya seluruh ekspektasi itu dipenuhi. Ekspektasi ekonomi pertambangan dan pengolahan mineral juga masih didominasi oleh logika linearitas, belum benar-benar sirkular, restoratif, apalagi regeneratif.
Membayangkan Masa Depan Pertambangan Indonesia
Untuk mendorong sektor pertambangan Indonesia menuju masa depan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan—mungkin bisa menjadi Good dalam satu dekade ke depan—jelas diperlukan kolaborasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan.
Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran regulasi nasional. Kebijakan harus dibuat lebih jelas, transparan, dan dapat diprediksi, mengurangi celah untuk korupsi dan interpretasi ganda. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan memastikan bahwa lembaga-lembaga pengawas memiliki sumber daya dan independensi yang cukup. Adopsi kerangka kerja internasional seperti EITI dalam cakupan yang lebih luas, termasuk pengungkapan kepemilikan manfaat dan kontrak secara proaktif, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mendorong perusahaan untuk mengadopsi standar internasional melalui insentif dan disinsentif, seperti rating kinerja ESG yang terintegrasi dengan perizinan, juga dapat menjadi langkah strategis. Terakhir, pemerintah perlu mengembangkan rencana transisi ekonomi yang komprehensif bagi masyarakat yang bergantung pada pertambangan, untuk memastikan keberlanjutan pascatambang.

Perusahaan perlu bergerak secara sukarela mengadopsi standar dan kerangka internasional. Ini berarti mengimplementasikan manajemen risiko ESG yang holistik, melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang proaktif, dan membangun mekanisme pengaduan yang kuat dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Berinvestasi dalam teknologi pertambangan yang bersih dan efisien serta praktik sirkular untuk minimalkan limbah dan memaksimalkan pemulihan sumber daya. Mengembangkan strategi penutupan tambang yang terintegrasi sejak awal operasi, dengan fokus pada reklamasi yang menghasilkan nilai lingkungan dan sosial. Perusahaan juga harus berinvestasi lebih besar dalam pengembangan kapasitas lokal, pengadaan lokal, dan diversifikasi ekonomi masyarakat, menciptakan nilai berkelanjutan di luar umur tambang.
Organisasi Masyarakat Sipil juga memiliki peran krusial sebagai penjaga dan pendorong perubahan. Mereka harus terus memantau dan melaporkan pelanggaran, memberikan data dan bukti yang kuat kepada pemerintah dan publik. Melakukan advokasi yang terinformasi untuk kebijakan yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih baik; memfasilitasi dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, dan membantu membangun kepercayaan dan mencari solusi bersama; dan memberikan pendidikan dan pemberdayaan kepada masyarakat terdampak, agar mereka memahami hak-hak mereka dan mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, juga adalah tugas yang sangat penting.
Masa depan pertambangan Indonesia bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini. Dengan berani mengadopsi praktik-praktik pertambangan yang melampaui sekadar kepatuhan kepada regulasi, Indonesia dapat mentransformasi sektor ini menjadi pendorong sejati bagi pembangunan berkelanjutan, meninggalkan warisan yang benar-benar positif bagi generasi mendatang, bukan hanya lubang dan kerusakan. Dan, pada saat yang sama, terus mendorong perubahan kebijakan dan regulasi agar semakin sesuai dengan tuntutan masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemakmuran yang lebih inklusif dan lingkungan yang lebih sehat—yang perlu kita semua dukung dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan demikian saja kita bisa meninggalkan Ugly and Bad Mining, menuju Okay or even Good Mining.
Bacaan terkait
Kiai Ulil dan Klaim “Penambangan Itu Baik, Asal Bukan Bad Mining”
Ulil, Tambang Batubara, dan Krisis Iklim
Setelah Heboh Ulil, Bahlil, dan Tahlil: Mungkinkah Pertambangan Hijau?
Ekonomi Politik Nikel di Indonesia [Belajar dari Artikel Trissia Wijaya dan Lee Jones (2025)]