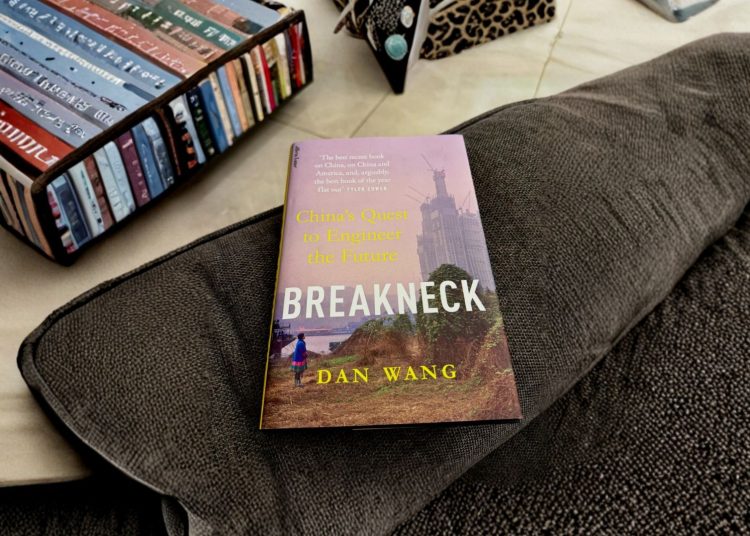Setiap ada buku tentang Tiongkok yang dinyatakan bagus, saya merasa harus membacanya. Bagaimanapun, nasihat untuk belajar hingga ke negeri Tiongkok benar-benar menarik untuk diperlakukan dalam makna literalnya—di mana buku bisa menjadi panduan awal untuk belajar sebelum berkesempatan untuk menyambanginya secara langsung dari waktu ke waktu.
Buku terbaru dalam topik ini, Breakneck China’s Quest to Engineer the Future, adalah sebuah eksplorasi mendalam tentang bagaimana Tiongkok berhasil mengelola pembangunan infrastruktur dan teknologi dengan kecepatan yang amat tinggi. Kecepatan ini secara kontras berbeda dengan Amerika Serikat (AS) yang sering terhambat oleh birokrasi dan proses hukum yang kompleks.
Dan Wang, penulisnya, adalah seorang analis teknologi yang tinggal di Tiongkok selama enam tahun, 2017–2023, setelah menempuh pendidikan filsafat di Universitas Rochester. Minatnya pada teknologi membuat ia penasaran pada kemajuan teknologi di kampung halaman orangtuanya, dan dunia kini mendapatkan hasil dari proyek pulang kampung yang sangat menarik.
Dengan rumah intelektual seperti Paul Tsai China Center di Universitas Yale dan sekarang di Hoover History Lab di Universitas Stanford, Wang memang raksasa pemikiran di usianya yang masih belia. Menurut saya, kekuatan utama buku pertama Wang ini ada pada keberhasilannya memadukan pengalaman empiris dengan analisis sosial dan politik untuk mengulas kedua negara ini dalam konteks perkembangan teknologi dan pembangunan masa depan global. Plus, dia menuliskannya dalam bahasa yang indah dan luar biasa berkelas.
Di awal buku, Wang menceritakan perjalanannya mengelilingi Tiongkok dengan sepeda—sesuatu yang menurut dia esensial agar bisa mendapatkan gambaran mendetail tentang suatu tempat. Dia tak datang ke tempat-tempat yang disebutkan sebagai lambang kemajuan ekonomi dan teknologi Tiongkok, melainkan ke wilayah-wilayah yang secara ekonomi masih dianggap tertinggal di negara tersebut. Dia amati dengan lekat perkembangannya, dari tahun ke tahun dia tuliskan satu surat yang menceritakan deru pembangunan di tempat-tempat itu, yang ia amati jauh lebih cepat daripada negara tempat ia belajar dan jadi rumah intelektualnya, AS.
Dari situlah, ia mulai mengembangkan gagasannya tentang perbedaan fundamental dalam pendekatan pembangunan antara Tiongkok dan AS yang menjadi benang merah buku ini. Tesis sentralnya sungguh elegan: persaingan fundamental abad ke-21 adalah antara ‘negeri insinyur’ versus ‘masyarakat pengacara’.
Melalui kerangka ini, Wang tidak hanya berhasil menjelaskan mengapa Tiongkok mampu membangun infrastruktur dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi juga mengapa AS tampaknya terjebak dalam stagnasi. Namun, buku Wang bukanlah sebuah glorifikasi untuk Tiongkok. Dengan ketajaman yang sama, Wang menelanjangi biaya kemanusiaan yang mengerikan dari mentalitas rekayasa sosial Beijing, sambil tetap mengakui pentingnya nilai-nilai pluralisme yang dijaga oleh tradisi hukum AS, meski sering kali menghambat kemajuan fisik. Karena itulah, bagi saya, buku adalah sebuah analisis komparatif yang esensial, membedah kekuatan dan kelemahan, serta ‘jiwa’ dari dua raksasa yang akan menentukan masa depan dunia.
Tiongkok: Negara yang Digerakkan oleh Para Insinyur
Argumen Wang bermula dari sebuah observasi sederhana namun mendalam tentang kepemimpinan Tiongkok. Sejak era Deng Xiaoping hingga Xi Jinping, eselon atas Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara sadar dan konsisten diisi oleh para insinyur. Xi Jinping sendiri belajar teknik kimia di Universitas Tsinghua, universitas sains paling bergengsi di Tiongkok. Mentalitas seorang insinyur, menurut Wang, adalah membangun. Ketika dihadapkan pada sebuah masalah, solusi naluriah mereka adalah “membangun jembatan, jalan raya, pusat data, pembangkit listrik, atau perumahan.”
Hasilnya terpampang nyata dan tak terbantahkan. Tiongkok kini memiliki jaringan jalan dua kali lebih panjang dari AS dan jaringan kereta cepat 20 kali lebih panjang dari Jepang. Negara ini menghasilkan tenaga surya dan angin hampir setara dengan gabungan seluruh dunia. Wang menyajikan kontras yang brutal: proyek kereta cepat Beijing-Shanghai sepanjang 1.300 km selesai dalam tiga tahun dengan biaya US$36 miliar, sementara proyek serupa di California, setelah 17 tahun, masih jauh dari selesai dengan estimasi biaya membengkak hingga US$128 miliar. Provinsi Guizhou—salah satu provinsi yang Wang kunjungi dengan sepedanya—yang dulu miskin kini dilintasi oleh jembatan-jembatan tertinggi di dunia dan jalan tol mulus, plus 11 bandara modern.
Di balik keajaiban infrastruktur ini terletak konsep kunci yang disebut Wang sebagai pengetahuan proses atau process knowledge. Ini bukanlah pengetahuan yang benar-benar bisa dikodifikasi dalam paten atau cetak biru, melainkan keahlian tacit yang lahir dari pengalaman praktis, dari iterasi berulang di lantai pabrik dan sepanjang rantai pasok. Pengetahuan inilah yang memungkinkan Tiongkok tidak hanya meniru, tetapi juga berinovasi dalam skala masif, menjadikan kota seperti Shenzhen sebagai hardware atelier bagi dunia.
Dominasi Tiongkok di industri kendaraan listrik, robot industri, panel surya (kini menguasai sekitar 90% pasar global), dan magnet dari logam tanah jarang adalah buah dari akumulasi pengetahuan proses selama puluhan tahun.
Namun, Wang juga dengan tegas menunjukkan sisi gelap dari mentalitas insinyur ini ketika diterapkan pada masyarakat. PKT memandang populasi sebagai sama seja dengan bahan bangunan lain, yang bisa dibentuk atau dihancurkan. Hasilnya adalah bencana rekayasa sosial seperti Kebijakan Satu Anak—dengan sterilisasi massal dan aborsi paksa yang menghilangkan jutaan anak perempuan—dan Kebijakan Nol-COVID yang brutal, dengan karantina wilayah berkepanjangan yang memisahkan keluarga dan menciptakan kelangkaan pangan.
Tragedi-tragedi ini, bagi Wang, adalah manifestasi dari kontrol keterlaluan dari PKT, dan ketidakpercayaan fundamentalnya terhadap rakyatnya sendiri, yang pada akhirnya membatasi potensi mereka untuk berkembang. Membaca bab 4 (tentang Kebijakan Satu Anak) dan 5 (mengenai COVID-19) buku ini bakal menyadarkan siapa pun betapa Wang adalah analis yang punya kekuatan luar biasa dalam pencarian data dan interpretasinya.
Amerika Serikat: Masyarakat yang Didominasi Para Pengacara.
Di seberang Pasifik, Wang menggambarkan AS sebagai masyarakat yang sejak kelahirannya telah dijalankan oleh para pengacara. Deklarasi Kemerdekaan, alih-alih sebagai manifesto pembebasan, sangat terasa seperti dokumen hukum. Saat ini, jumlah pengacara di Kongres AS jauh melampaui para profesional STEM—berbeda secara diametrikal dengan isi PKT. Jika insinyur terobsesi pada hasil, maka pengacara, menurut Wang, terobsesi pada proses. Mentalitas ini, yang awalnya bertujuan melindungi hak-hak individu, telah bermutasi menjadi apa yang disebutnya sebagai litigious vetocracy—sebuah sistem di mana hampir setiap proyek pembangunan dapat diblokir atau ditunda tanpa batas waktu melalui tuntutan hukum.
Para pengacara, tulis Wang, jauh lebih mahir dalam menghalangi daripada membangun. Proyek-proyek vital sering kali terhenti karena gugatan atas polusi suara, polusi cahaya, isu lingkungan, atau masalah zonasi. Hasilnya adalah tumpukan proyek yang mangkrak, infrastruktur yang menua dan tidak fungsional, krisis perumahan, dan anggaran pemerintah yang membengkak.
Seiring dengan deindustrialisasi dan outsourcing, AS tidak hanya kehilangan pabrik, tetapi juga pengetahuan proses yang krusial, sebuah kerugian yang dampaknya terasa nyata selama pandemi COVID-19 ketika negara itu kesulitan memproduksi barang-barang esensial, lantaran sudah sangat nyaman, bahkan kecanduan, dengan konsumsi barang-barang impor.
Wang melacak pergeseran ini hingga ke tahun 1960-an. Jika pengacara era New DealFranklin D. Roosevelt adalah para dealmakers yang fokus pada penyelesaian masalah, maka generasi pasca-1960-an cenderung menjadi regulator dan litigator yang memprioritaskan prosedur dan penentangan terhadap tindakan-tindakan dari korporasi dan pemerintah—yang memang kerap juga membahayakan masyarakat.
Namun, Wang tidak sepenuhnya mengutuk sistem ini. Manfaat terbesar dari masyarakat pengacara adalah terjaganya pluralisme dan inklusi—kemampuan untuk memastikan lebih banyak suara didengar dan debat yang lebih kuat terjadi. Para pengacara di AS berfungsi sebagai penjamin pluralisme, sebuah katup pengaman yang, agaknya, tidak dimiliki oleh Tiongkok. Oleh karenanya, ketika Donald Trump berkuasa dan hukum sama sekali tidak dihargai, seluruh dunia bisa melihat betapa centang perenangnya kondisi AS sekarang.
Timbangan
Kekuatan terbesar buku ini jelas terletak pada metafora sentralnya. Kerangka negara insinyur versus masyarakat pengacara adalah alat analisis yang luar biasa kuat, segar, intuitif—dan mustahil dilupakan oleh pembaca buku ini atau siapa pun yang mendengarnya. Ia berhasil menyibak kabut ideologis dan memberikan penjelasan yang koheren tentang mengapa kedua negara berperilaku seperti yang mereka lakukan. Alih-alih terjebak dalam label kapitalis versus sosialis atau demokratis versus autoritarian—yang menurut Wang sudah tidak lagi relevan—ia memilih berfokus pada fungsi dan hasil yang dapat diamati.
Kedua, buku ini memiliki keseimbangan dan nuansa yang mengagumkan. Wang tidak terjebak dalam glorifikasi atau demonisasi yang simplistis kepada dua negara itu. Ia memuji pencapaian material Tiongkok yang spektakuler sambil tanpa ampun juga melancarkan kritik atas pelanggaran hak asasi manusianya. Ia menelanjangi stagnasi pembangunan di AS, namun menghargai nilai fundamental dari pluralisme dan kebebasan individu yang dilindunginya. Keseimbangan ini menjadikan buku ini sungguh bacaan yang kredibel dan memprovokasi pemikiran.
Ketiga, penekanan Wang pada konsep pengetahuan proses merupakan kontribusi intelektual yang signifikan. Wang mengingatkan kita bahwa teknologi sejati bukanlah sekadar alat atau instruksi tertulis, melainkan keahlian yang tertanam dalam pengalaman manusia. Ini adalah wawasan krusial bagi para pembuat kebijakan di Barat yang berpikir bahwa inovasi dapat dicapai hanya melalui investasi dalam R&D tanpa membangun kembali basis manufaktur dan SDM yang kuat untuk menjalankannya.
Di sisi lain, metafora sentral yang menjadi kekuatannya juga bisa mengarah pada generalisasi berlebih. Apakah semua masalah Tiongkok dapat diatribusikan pada model mental insinyur, dan semua kebuntuan di AS pada mentalitas pengacara? Tentu ada seabrek faktor lain yang juga penting. Saya membayangkan lintasan sejarah yang berbeda, ideologi politik yang mendasari, dan struktur sosial yang kompleks—yang jelas tidak sepenuhnya tertangkap oleh, dan terungkap dari, dikotomi mentalitas profesional ini.
Selain itu, buku ini agaknya masih jauh lebih kuat dalam diagnosis daripada dalam preskripsi—bagi para pembaca yang mencarinya. Wang secara meyakinkan mengidentifikasi masalah stagnasi di AS, tetapi kurang memberikan peta jalan yang konkret tentang bagaimana masyarakat pengacara dapat belajar untuk membangun kembali tanpa mengorbankan komitmennya pada proses hukum dan hak-hak individu. Bagaimana cara memotong birokrasi dan hambatan hukum tanpa membuka pintu bagi eksploitasi lingkungan atau perampasan hak milik? Pertanyaan-pertanyaan sulit ini belum sepenuhnya terjawab.
Renungan Akhir
Ketika menyelesaikan halaman terakhir Breakneck, saya merasa bahwa buku tidak sekadar memberikan gambaran tentang bagaimana Tiongkok membangun masa depannya dengan cara teknis dan cepat, tetapi juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dengan perlindungan hak dan kemanusiaan, serta perlunya adaptasi dan pembelajaran bersama antara dua raksasa dunia demi kemajuan dan kedamaian global.
Wang menyarankan bahwa kedua negara bisa belajar dari kelebihan masing-masing. AS harus meningkatkan kemampuan teknis dan pragmatisme dalam pembangunan dengan tetap mempertahankan kaidah hukum dan kebebasan, sedangkan Tiongkok perlu menambah dimensi perlindungan hukum dan hak sipil agar pembangunan tidak mengorbankan hak-hak dasar rakyat.
Masa depan persaingan antara kedua negara itu—dan dampaknya terhadap seluruh negara lain—jelas bukan hanya soal ideologi atau kekuatan militer, melainkan bagaimana mereka dan kita semua mampu merekonstruksi sistem sosial, politik, dan ekonomi mereka agar adaptif menghadapi tantangan global yang terus berubah. Buku ini, ketika saya menutup halaman terakhirnya, tak terasa lagi sebagai buku tentang teknologi sebagaimana yang saya bayangkan di awal. Wang begitu berhasil mengajak pembaca memahami perbedaan fundamental dalam cara negara membangun masa depan mereka melalui lensa budaya, politik, dan teknologi.
Karenanya, membaca buku ini dari Indonesia, saya bertanya-tanya, kalau benak sekaliber Wang mengupas kondisi pembangunan Indonesia hingga sekarang, apa yang bakal dia simpulkan. Saya punya jawaban sementaranya. Tetapi itu untuk dituliskan di tempat lain.