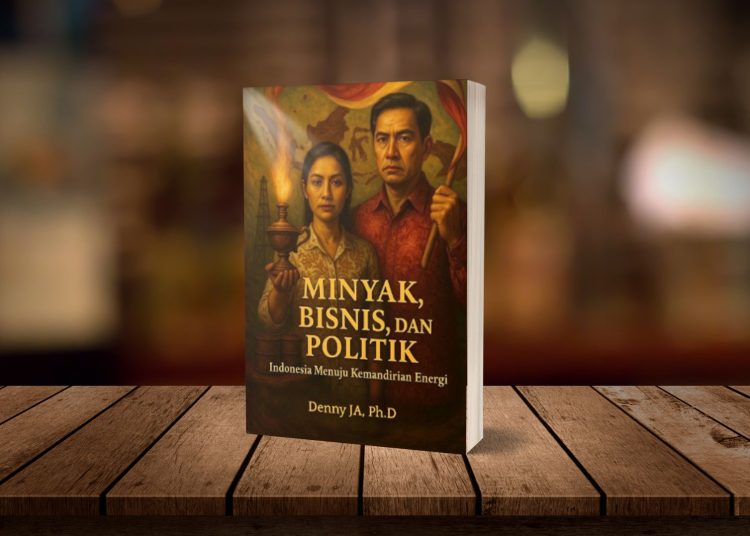Di halaman-halaman awal buku Minyak, Bisnis, dan Politik, Denny JA melukis sebuah adegan yang menghantui dari Cepu: seorang petani dan seorang tukang becak menambang minyak mentah dengan “sasis mobil tua, ember, dan keyakinan”. Ini adalah potret telanjang dari paradoks energi Indonesia—sebuah bangsa yang duduk di atas kekayaan energi, namun rakyatnya harus menggali sisa-sisa mimpi mereka dengan tangan telanjang.
Buku ini, sebuah kompilasi esai dan pidato, tiba di saat yang tepat. Penulisnya bukan ‘sekadar’ pengamat; karena kini ia adalah Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi, subholding yang menjadi ujung tombak eksplorasi dan produksi minyak Indonesia. Ini membuat buku tersebut bukan sekadar analisis, melainkan sebuah artefak bisnis dan politik sekaligus—separuh manifesto, separuh justifikasi, dari orang yang bisa dikatakan ‘mendadak minyak’.
Denny JA jelas menulis dengan gaya seorang penyair yang merangkap sebagai konsultan politik, dua hal yang memang melekat pada hidupnya. Ia meromantisasi energi dengan kekuatan penyair. Baginya, energi adalah ‘darah bangsa’, ‘detak jantung peradaban’, dan barang siapa yang menguasainya, ‘menggenggam denyut peradaban’. Tetapi, ia juga konsultan politik luar biasa andal, sehingga pesan-pesannya itu tidak bisa dikatakan datang dari ruang hampa kekuasaan.
Inti dari tesisnya adalah sebuah seruan kebangsaan: Kemandirian Energi. Ia melihat tragedi Sri Lanka, yang runtuh tanpa energi, dan Venezuela, yang hancur oleh ‘kutukan sumber daya’, sebagai peringatan keras. Solusinya, bagi Denny JA, adalah sebuah misi yang ia sendiri sebut ‘Mission Impossible’: Misi luar biasa berat untuk mengembalikan produksi minyak Indonesia ke 1 juta barel per hari pada tahun 2029.
Bagi saya, di sinilah letak jantung persoalan buku ini. Ia adalah sebuah dokumen yang secara brilian mendiagnosis penyakit dunia, termasuk kita yang berada di Indonesia, pada abad ke-20 lampau. Namun, dengan keras kepala menawarkan resep dari abad yang sama, bukan melihatnya dari persoalan dan solusi yang lebih masuk akal bagi abad ke-21 di mana kita semua hidup sekarang.
Dari kacamata energy quadrilemma—sebuah kebijakan energi yang waras harus menyeimbangkan empat pilar: Keamanan, Keterjangkauan, Keberlanjutan Lingkungan, dan Keadilan Transisi. Buku ini, sayangnya, terobsesi pada satu pilar: Keamanan, yang, entah sengaja atau tidak, ia gelembungkan sebagai kedaulatan, atau setidaknya kemandirian. Seluruh arsitektur argumennya dibangun untuk menopang target satu juta barel itu. Pilar-pilar lain, terutama Keberlanjutan Lingkungan dan Keadilan Transisi, diperlakukan sebagai renungan, sebuah kemewahan yang bisa dipikirkan nanti bila sempat.
Jangan salah. Buku ini penuh dengan pengakuan atas krisis iklim. Ia berbicara tentang ‘Bumi yang Terluka’, perlunya ‘Peralihan ke Energi Hijau’, dan bahkan memuji Ørsted, perusahaan Denmark yang beralih dari batu bara ke energi angin. Namun, semua ini hanya muncul di bagian pemanasan. Ketika sampai pada bagian Lampiran Pidato—di mana posisi resmi penulis sebagai Komut PHE berbicara—retorika hijau itu menguap. Hilang, sirna, entah ke mana.
Yang tersisa adalah fokus tunggal pada minyak.
Transisi energi hijau, dalam proposal konkretnya, dilihat bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai jembatan atau sesuatu yang akan didanai oleh lebih banyak minyak. Ia mengusulkan alokasi “20% keuntungan tiap sumur baru untuk green energy seed fund“. Ini adalah sebuah logika yang secara fundamental cacat dari perspektif iklim: untuk menyelamatkan diri dari lubang, kita harus menggalinya lebih dalam terlebih dahulu. Andreas Malm dan Wim Carton sudah menghancurleburkan usulan ini lewat kitab mereka dari tahun lalu, Overshoot: How the World Surrendered to Climate Breakdown.
Buku ini bukannya tidak mengakui potensi energi terbarukan Indonesia yang luar biasa—ribuan gigawatt dari surya saja—tetapi dengan cepat mengesampingkannya sebagai ‘belum optimal’. Misi mustahil yang jelas sejati bagi bangsa ini—yaitu memanfaatkan sepersekian persen saja dari potensi raksasa itu—bahkan tidak pernah dipertimbangkan. Seluruh imajinasi kolektif soal energi yang ia serukan diarahkan untuk mengejar target produksi minyak.
Kritik paling tajam dari buku ini sebetulnya ditujukan pada Pertamina sendiri. Ia mengajukan pertanyaan provokatif: Akankah Pertamina mengikuti jalan Aramco (raksasa Saudi yang sungguh efisien) atau Petrobras (raksasa Brasil yang limbung terjerat korupsi)?
Tetapi, barangkali, ini adalah kegagalan konseptual terbesar buku ini. Dari perspektif keberlanjutan perusahaan, pertanyaan ini, menurut saya, salah sasaran. Memilih antara Aramco dan Petrobras adalah memilih di antara dua model National Oil Company yang sama-sama berakar pada ekonomi ekstraktif abad lalu. Aspirasi seperti ‘Make Pertamina Great Again‘ adalah seruan nostalgia untuk kembali ke era keemasan 1970-an, bukan ajakan untuk melakukan lompatan ke masa depan.
Buku ini, saya kira, nyaris menemukan jawabannya ketika menyebut Ørsted, model perusahaan energi yang berhasil melakukan transformasi eksistensial. Namun, ia kemudian memalingkan muka dengan segera. Lebih mudah membayangkan Pertamina menjadi Aramco—dinosaurus yang sekarang lebih ramping dan cepat seperti T-Rex—daripada membayangkannya berevolusi menjadi binatang yang sepenuhnya baru dan bisa sesuai dengan zamannya.
Buku ini juga bertanya, “Apakah Pertamina Bisa Selamat di Era Tanpa Minyak?” Namun, jawaban yang tersirat dari 200 halaman sisanya adalah: “Mari kita pastikan era tanpa minyak itu tidak datang terlalu cepat.” Sebuah jawaban yang membuat saya mengembuskan nafas panjang. Namun, demi bisa memahami buku ini secara utuh, saya meneruskan membacanya.
Lantas, bagaimana Misi Mustahil ini akan dicapai? Jawabannya adalah teknologi. Buku ini penuh dengan optimisme teknokratis: Enhanced Oil Recovery (EOR), fracking, Artificial Intelligence (AI), juga digital twins. Namun, bermacam teknologi di sini tidak digunakan untuk memecahkan quadrilemma yang nyata kita hadapi. Teknologi malah digunakan untuk memperdalam ketergantungan. AI tidak dipakai untuk memodelkan jaringan smart-grid untuk listrik tenaga surya, melainkan untuk “memahami perilaku reservoir tua.”
Ketika selesai membaca paragraf terakhir, saya menyadari bahwa buku ini pada akhirnya adalah sebuah cermin sempurna dari pemahaman mayoritas pemegang tampuk kekuasaan politik dan bisnis di Indonesia. Sebuah bangsa yang trauma oleh berbagai krisis di masa lalu dan gamang dengan kondisi geopolitik dan geoekonomi masa sekarang, sehingga memutuskan untuk memprioritaskan ‘kemandirian’ dan ‘kedaulatan’ energi di atas segalanya—sambil melupakan bahwa sumber-sumber energi terbarukanlah yang sejatinya bisa menghasilkan kemandirian dan kedaulatan yang hakiki. Hasil akhirnya: ia adalah manifesto Petro-Nasionalisme yang jujur dan terbuka.
Kekuatan buku ini, tentu saja, adalah kejujurannya dalam memaparkan luka: korupsi, mafia impor, dan ketidakadilan di Cepu. Namun, tragedinya adalah kegagalan imajinasi. Ia tidak mampu membayangkan masa depan Indonesia yang hebat tanpa minyak. Atau bahkan sekadar membayangkan Pertamina menjadi perusahaan energi yang kompatibel dengan tuntunan masa depan.
Misi mustahil yang sejati bukanlah mengejar 1 juta barel minyak dalam 4 tahun. Misi mustahil yang sejati adalah melepaskan bangsa ini dari kecanduan parahnya terhadap energi fosil, yang telah begitu lama mendefinisikan kekuasaan, politik, dan bisnisnya. Dan dalam misi yang paling krusial ini, buku ini, terlepas dari segala niat baiknya, agaknya memilih untuk tidak berpartisipasi. Mungkin saja, kalau Denny JA adalah komisaris utama Pertamina Geothermal Energy, pesan-pesannya akan berbeda, dan bukunya bakal mengundang apresiasi yang lebih tinggi dari orang-orang seperti saya.